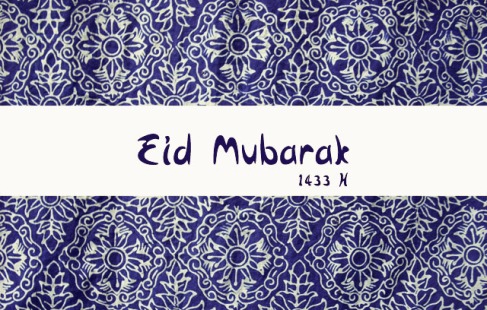Aku bertemu Malaikat Maut. Bayangkan betapa kagetnya aku ketika ia tiba-tiba muncul di hadapanku ketika aku sedang membaca diktat kuliah di kamar kos. Begitu terkejutnya diriku hingga aku bahkan tak sempat berteriak ‘Wuaa!!’ atau semacamnya ketika sesosok laki-laki berdiri di satu meter di depanku. Aku hanya bisa tersentak hingga diktat kuliah di tanganku terjatuh ke atas lantai.
“Selamat malam,” sapanya.
“Si-siapa kamu?”
“Aku Malaikat Maut.”
“Hah?”
Pembicaraan yang aneh sekali. Di kamar kos yang terkunci rapat, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai Malaikat Maut.
“Aku datang untuk memberitahumu waktu kematianmu,” ujarnya.
“Hah?” Aku benar-benar tak mengerti, hanya bisa terperangah dan memperhatikan laki-laki di hadapanku itu. Pria yang mengaku Malaikat Maut itu terlihat seperti laki-laki berusia tiga puluh tahunan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Selain kemejanya, semua yang dikenakannya serba hitam, termasuk dasi dan sepatunya. Sekilas ia terlihat seperti seorang eksekutif muda, atau tokoh film Men In Black, minus kacamata hitam.
Aku melirik ke arah pintu kamar. Kuncinya menggantung, dan aku ingat aku baru saja menguncinya beberapa saat yang lalu. Aku melirik ke jendela. Bukan hanya jendela itu terkunci, tapi juga teralisnya hanya mungkin dilewati seekor kucing atau yang lebih kecil dari itu. Dan kamarku ada di lantai dua.
Seolah membaca pikiranku, pria itu berkata, “Kamu ingin tahu aku masuk darimana?”
“Eh…?”
Aku tak belum sempat menjawab ketika ia mengaskan tentang dirinya, “Aku Malaikat Maut, tidak perlu masuk lewat pintu,” ujarnya sambil tersenyum.
“Aku di sini untuk memberitahumu waktu kematianmu,” kemudian ia mengeluarkan semacam catatan dari saku jasnya. “Yudhistira Harimurti bin Bambang Prakoso…,” ia menyebut namaku. “…waktu kematianmu…,” katanya sambil membolak-balik halaman buku kecil di tangannya, “…17 Desember 2012, pukul 15:22. Tiga hari lagi.”
“Se-sebentar…!” sanggahku.
“Apa?”
“Anda ini siapa sih? Tahu-tahu masuk, nggak tahu dari mana, ngaku-ngaku Malaikat Maut, terus ngasih tahu saya akan mati tiga hari lagi. Anda disuruh siapa buat ngerjain saya? Anton? Irfan? Ridho?”
“Kamu tidak percaya?”
“Nggak.”
“Sama sekali?”
“Sama sekali.”
Ia membuka buku kecilnya sekali lagi, kemudian berkata, “Suciwati binti Hindun, pemilik rumah kos ini, akan meninggal dunia karena serangan jantung besok pagi pukul delapan lewat dua belas menit.”
“Hah?”
“Orang-orang akan membawanya ke rumah sakit, tapi tidak akan sempat.”
Aku tidak tahu harus bilang apa menanggapi lelucon yang tidak lucu ini.
“Besok saya akan datang lagi,” ujarnya sambil menutup buku ‘catatan kematian’ itu dan memasukkannya ke saku jasnya.
Tok… tok… tok…! Seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku menoleh ke arah pintu. Begitu aku memalingkan kepalaku lagi, pria itu sudah tidak ada.
Aku merinding.
“Yudi…!” panggil suara dari balik pintu itu. Itu suara Bu Suci. Aku segera membuka pintu.
“Kenapa, Bu?”
“Kamu…,” ia bertanya sambil menatapku dalam-dalam. Apakah ia mendengar pembicaraanku dengan ‘Malaikat Maut’ barusan? Menghadapi orang yang kamu mendengar kabar bahwa ia akan mati besok pagi membuatmu gugup. Tapi kemudian ia melanjutkan kata-katanya, “…belum bayar kos kan?”
Aku menghela nafas lega. Aku memperhatikan pemilik rumah kosku ini. Usianya sudah paruh baya, keriput terlihat di pipi dan sudut matanya, juga di keningnya. Apakah rambutnya sudah beruban? Aku tidak tahu, karena ia selalu terlihat mengenakan jilbab ringkas khas ibu-ibu. Yang pasti ia selalu nampak segar bugar dan bersemangat. Ia selalu bangun lebih dulu sebelum para pembantu rumah kos ini bangun, memasak, mencuci, dan menyapu. Ia sering terlihat bekerja lebih keras dibanding pembantunya sendiri.
“Heh, kok bengong?” Bu Suci membangunkan lamunanku.
“Eh, uh… iya. Besok ya bu. Belum ke ATM nih.”
“Ya sudah, jangan telat ya. Inget, lewat tanggal 10 kena denda. Tapi nggak apa-apa sih kalo kamu mau sengaja bayar lebih. Hehehe…”
“Ehehehe…,” aku tertawa canggung. Sulit untuk tertawa mendengar kelakar dari orang yang kamu tahu akan meninggal dunia beberapa belas jam lagi.
“Ngomong-ngomong, Bu…,”
“Ya?”
“Ibu… sehat-sehat aja kan?”
Bu Suci menatapku seakan aku orang aneh. Hampir tiga tahun aku tinggal di sini, baru pertama kali ia mendengar aku bertanya kabar.
“Yang nggak sehat itu kamu, diajak ngomong malah bengong. Hahaha…”
“Ahahaha…,” lagi-lagi aku tertawa canggung.
“Sudah ah, mau nagihin yang lain.”
“Oh, iya. Oke sip, Bu.”
Bu Suci melangkah pergi. Aku memperhatikannya dari jauh sambil merenungi kata-kata ‘Malaikat Maut’ tadi. Aku tidak ingin percaya, tapi bagaimana kalau orang itu benar? Bagaimana kalau ia benar-benar Malaikat Maut? Ia datang dan pergi dengan cara yang ajaib seperti itu. Kalau aku tidak sedang berhalusinasi, apa lagi penjelasannya?
Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi. Aku baru bisa terlelap setelah subuh.
Aku bangun ketika matahari mulai meninggi. Aku meloncat dari kasur dan berlari ke luar kamar, kemudian ke tangga, turun ke lantai satu. Tanpa sadar, aku berteriak, “Bu Suci!”
Semua mata tertuju padaku. Anton yang sedang menyuap nasi, berhenti mengunyah, matanya menatapku heran. Irfan yang sedang membaca buku juga berhenti membaca dan menatapku dengan tatapan yang sama herannya dengan Anton. Bu Suci tak kalah kagetnya. Tangannya yang sedang menumis sayuran berhenti sejenak. Ia menatapku dengan ekspresi bingung.
“Kenapa, Yud?” tanya Bu Suci. Suasanya menjadi sangat canggung.
“Euh… uangnya… nanti sore aja ya,” ujarku mencoba mencairkan suasana.
“Oh, santai aja… Sarapan dulu, Yud!” Agaknya aku berhasil. Anton dan Irfan melanjutkan apa yang sedang mereka kerjakan tanpa berkata apa-apa.
Aku melihat jam dinding. Pukul delapan lewat lima belas menit. ‘Jam kematian’ yang dijanjikan pria misterius semalam sudah lewat. Tidak terjadi apa-apa. Apakah yang semalam hanya orang iseng? Atau aku hanya mimpi?
Ah, sudahlah. Aku sudah terlambat kuliah pagi. Aku terpaksa melewatkan sarapan dan bergegas pergi ke kampus.
*****
Tepat selepas kuliah, ponselku berdering. Nama “Anton_Jeprut” muncul di layar. Perasaanku tidak enak, dan semakin tidak enak ketika Anton memintaku segera pulang ke kosan dengan suara yang seperti memendam sesuatu. Aku tak banyak bertanya dan segera mengiyakan.Hatiku tak karuan. Aku takut apa yang dikatakan pria misterius semalam benar-benar terjadi.
Jantungku serasa turun tiga senti ketika kulihat ada bendera kuning di depan pintu rumah kosku. Orang-orang berkerumun. Doa-doa dibacakan. Suara isak tangis terdengar di antara riuh rendah. Aku tak perlu diberi tahu siapa yang meninggal hari itu.
Tubuhku gemetar. Irfan menepuk pundakku dan menatapku tanpa bicara apa-apa. Ia memberiku segelas air putih. Sambil gemetar kuminum air itu. Air putih terberat yang pernah masuk ke dalam kerongkonganku.
Lututku lemas. Dengan langkah kaki yang masih gemetar aku masuk ke dalam kamar. Aku merangkak ke ujung tempat tidur, kemudian meringkuk di sana. Aku bisa melihat wajahku di dalam cermin yang menempel di lemari baju. Pucat pasi.
Betapa tidak. Malaikat Maut datang kepadaku, memberi tahu kematian pemilik rumah kosku dan apa yang dikatakannya sungguh-sungguh terjadi. Berarti, apa yang dikatakannya tentang kematianku juga akan terjadi. Aku akan mati besok sore.
Aku akan mati.
Besok sore.
Aku.
Akan.
Mati.
Besok.
Sore.
Aku takut setengah mati. Barangkali kata itu sekarang artinya sudah menjadi harfiah, mengingat betapa dekatnya aku dengan kematian. Seluruh tenaga di tubuhku lenyap. Aku bahkan tak sanggup menangis. Hanya ketakutan luar biasa menyelimutiku.
Tiba-tiba, terdengar suara yang tak asing. “Bagaimana?” tanya suara itu.
Aku menoleh dan mendapati sang Malaikat Maut berdiri di sudut kamarku.
“Jam di dapur itu dimajukan sepuluh menit,” ujarnya. Ia menjelaskan mengapa Bu Suci masih hidup ketika aku menemuinya tadi pagi.
“Beneran ya?” tanyaku. Aku tak ingin percaya. Aku masih ingin hidup. Terlalu banyak yang belum aku lakukan dalam hidup ini. Terlalu banyak kesalahan yang kuperbuat pada orang lain. Terlalu sering aku mengecewakan orang tuaku.
“Kamu sudah lihat sendiri buktinya, kan?” suaranya terdengar begitu santai. Pastinya karena ia adalah Malaikat Maut. ia tidak merasakan ketakutan seperti manusia.
“Aku belum siap.”
“Kematian tidak pernah menunggu.”
*****
Hari itu, aku tak sanggup makan. Lebih tepatnya, aku tak ingin makan. Lapar tidak lagi terasa ketika kamu tahu kamu akan mati dalam beberapa puluh jam.
Sebelum Malaikat Maut itu pergi, ia memberiku nasihat. Ia bilang, ‘Angan-angan manusia terlalu panjang dibandingkan usianya’. Oh, betapa ia benar. Aku tak sanggup lagi bermimpi tentang masa depanku. Di hadapan kematian, cita-citaku menjadi arsitek hilang bagai debu ditiup angin. Di hadapan kematian, segalanya runtuh, yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar penting.
Adalah kata-kata terakhir sang Malaikat Maut yang menjadi satu-satunya sumber energiku. Ia bilang, ‘Kali selanjutnya kita bertemu, adalah saat kematianmu. Kamu punya dua puluh tujuh jam. Manfaatkanlah dengan baik’.
Lantas, bagaimana aku memanfaatkan dua puluh tujuh jam terakhir dalam hidupku?
Pertama-tama, aku sholat. Aku ingin membayar semua sholat yang kutinggalkan. Aku pernah mendengar dari guru agamaku, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib dibayar di lain waktu. Bodohnya aku menunda-nunda hingga sekarang.
Aku sholat subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh lagi. Begitu seterusnya hingga malam tiba. Di hadapan kematian, seseorang bisa jadi sangat religius, melebihi seseorang yang baru pindah agama.
Entah sudah berapa banyak sholat yang kutinggalkan. Kukerjakan saja sekuatnya. Hingga pada sholat entah keberapa puluh, aku ambruk. Aku berusaha berdiri, tapi aku ambruk lagi. Pandanganku nanar. Aku jatuh pingsan.
Aku dibangunkan oleh adzan subuh. Badanku masih lemas, tapi keinginanku untuk pergi ke masjid membuatku berdiri. Sholat subuh terakhirku, kataku kepada diriku sendiri dalam hati. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kekhusyukan sholatku saat itu.
Seusai sholat, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku masih punya hutang pada Bu Suci. Aku tahu aku akan menyusulnya sebentar lagi. Tapi urusan bayar kos adalah hutang di dunia, dan aku tak ingin bawa-bawa hutang ke akhirat. Kabarnya, urusan seseorang ‘di sana’ bisa rumit jika mati meninggalkan hutang yang belum terbayar.
Maka jadilah aku pergi ke ATM, mengambil semua uang yang kupunya. Kumasukkan uang kosku ke dalam amplop. Kutitipkan kepada Anton. Ia terheran-heran dan bertanya, mengapa tidak hari lain saja. Aku bilang aku mau pergi. Ia tak paham, tapi amanah itu diembannya juga.
Waktuku kurang dari sembilan jam lagi. Kubongkar kamarku, kucari barang-barang pinjaman yang masih tersisa. Kuambil kamera digital milik Oscar yang kupinjam untuk dokumentasi Wisuda seminggu lalu. Kubawa buku biografi Frank Loyld Wright milik Widya. Kunyalakan sepeda motor dan kukenakan helm yang kupinjam dari Tyo. Aku akan mengembalikan barang-barang ini.
Aku memacu motorku di jalanan yang lengang. Biasanya aku tak suka ngebut, tapi kali ini berbeda. Aku tahu aku tak akan mati di sini, jadi kupuas-puaskan saja ngebut di jalanan. Kunikmati hembusan angin jalanan di tubuhku untuk terakhir kalinya. Untuk pertama kali sekaligus yang terakhir kalinya, aku paham perasaan orang yang suka ngebut di jalan. Aku tak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Di hadapan kematian, semua terasa luar biasa.
Setelah mengembalikan barang-barang pinjaman, terbesit keinginan untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah kusakiti. Aku hanya punya kurang dari enam jam untuk melakukan itu semua. Aku menepi di atas jembatan layang. Dari sana, aku mulai menelepon temanku satu per satu.
Aku menelepon Ruslan, yang aku pernah menghilangkan satu dari koleksi komik Tin-Tin kesayangannya. Aku menelepon Abdi, yang hubunganku dengannya jadi renggang sejak aku mengerjainya secara kelewatan. Aku menelepon Nina, yang pernah kucemarkan namanya karena aku menulis aibnya di internet. Kemudian, aku menelepon teman-temanku yang lain. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk meminta maaf lewat telepon.
Terakhir, aku menelepon orang tuaku.
“Halo?”
“Mama ada, dek?”
“Mas Yudi ya? Sebentar… Mamaah…! Mas Yudi nih…!”
“Halo, Ma?”
“Kenapa, Yud?”
Aku terdiam sejenak.
“Halo? Yud?”
“Mama… Yudi… mau minta maaf. Selama ini Yudi udah sering bikin Mama kecewa. Yudi gak bisa kasih apa-apa buat Mama. Yudi belum bisa bikin Mama bangga. Yudi…,” air mataku mulai menetes di pipi.
“Kamu kenapa, sayang?”
“Gak apa-apa…,” kataku sambil terisak. Ah, bahkan di saat-saat terakhir aku masih berbohong, bodoh sekali. “Makasih ya, Ma. Yudi sayang Mama,” itulah kata-kata terakhirku kepada ibuku. Aku abaikan suaranya yang memanggil-manggil namaku dari balik telepon. Kututup teleponnya, kumatikan ponselku, dan kulemparkan dari atas jembatan layang. Aku melihatnya jatuh dan terlindas beberapa mobil yang lewat di bawah sana.
Aku kembali ke kamar kosku. Tidak sampai satu jam lagi, Malaikat Maut akan datang mencabut nyawaku. Aku berusaha meyakinkan diri, tapi siapakah yang siap menghadapi kematian yang ada tepat di depan mata? Inikah yang dirasakan para prajurit di medan perang, yang tetap menerjang meskipun itu berarti kematian yang pasti?
Aku tak bisa menyembunyikan ketakutanku. Hawa dingin menjalar ke tengukku, membuatku menggigil. Tak lama kemudian, Malaikat Maut datang.
Seperti sebelumnya, ia terlihat santai meski mengenakan setelan jas lengkap.
“Sudah siap?” Tanyanya.
“Mana ada orang siap menghadapi kematian,” jawabku.
“Kamu tidak ingin menyatakan cinta pada seseorang terlebih dahulu?”
“Cinta…?” aku baru sadar, aku tak pernah memikirkannya. Aku berpikir sejenak. Tak ada satupun nama yang terlintas di kepala. “Tidak,” lanjutku singkat.
Keheningan menyelimuti udara. Rasanya jarum jam berjalan lebih lambat dari biasanya. Malaikat Maut memecah keheningan dengan berkata, “Sudah waktunya.”
Ia mengeluarkan sepucuk pistol dari balik jasnya.
“Pistol? Aku pikir…”
“Kamu pikir aku akan menggunakan sabit besar? Kamu terlalu banyak nonton film.”
Malaikat Maut mendekat kepadaku dan dengan perlahan meletakkan moncong pistol itu di dahiku. Aku bisa merasakan besi yang dingin di kulitku. Pistol itu nampak begitu nyata. Terlalu nyata. Aku pikir aku akan mengalami pengalaman yang lebih terasa magis, tapi semua ini terasa begitu… jasmaniah.
Aku tak bisa menyembunyikan ketakutanku. Seluruh tubuhku bergetar. Keringat dingin mengucur. Aku memejamkan mata, berusaha mengucap doa. Kemudian….
Dor!
*****
Di suatu perumahan, terlihat orang-orang berkumpul.
“Mundur! Mundur!” kata sebuah suara. Sementara itu, seseorang berseragam dan mengenakan sarung tangan memasang pita berwarna kuning bertuliskan “DILARANG MELINTAS GARIS POLISI”
Seorang polisi bertanya kepada polisi lainnya, “Bagaimana?”
“Pertama-tama, kita harus selidiki pistol itu…”
Sementara itu di tempat lain, Anton dan Irfan sedang bercakap-cakap.
“Gak nyangka ya,” ujar Irfan.
“Iya. Ternyata dia nitip bayaran kosan itu karena ini,” kata Anton.
Suasana haru biru. Masing-masing dari mereka merasakan pilu, melepas kepergian sahabat mereka yang tiba-tiba.
Esok harinya, terdapat berita di sebuah koran lokal. Judul berita itu:
“Seorang Mahasiswa Bunuh Diri di Kamar Kos”



 Seekor naga hidup di puncak gunung. Hari ini, kami akan membunuhnya.
Seekor naga hidup di puncak gunung. Hari ini, kami akan membunuhnya.